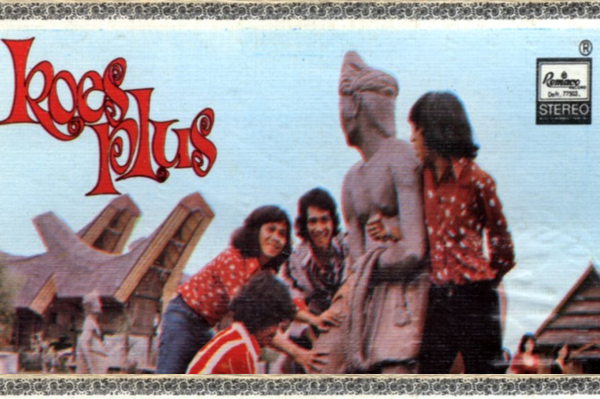Pada suatu hari di salon…
Siang yang terik di sebuah kampung kota kecil yang dekat dengan Ibu kota Jawa Barat, burung-burung sawah berceracau memecah langit. Sesekali ia terhenti di atas genting rumah warga. Barangkali sekadar menyimak dunia yang berlari. Tunggang langgang tak terdefinisi.
Di kampung tersebut masih mudah ditemui bentangan sawah dan sederetan pepohonan hijau beragam varian yang ditepinya dialiri sungai yang bermuara menuju entah. Ada yang bilang ke atas dan ada juga yang mengatakan ke atasnya lagi. Tak lagi penting ia akan bermuara ke mana, namun hal semacam itu merupakan kegembiraan tersendiri mengingat saya banyak menghabiskan hari di kota besar macam Jakarta.
Ya, kota yang tak akan pernah sembuh dari sakitnya. Kota yang penuh dengan labirin ketidakmungkinan. Kota yang layak ditinggalkan sekaligus dihidupi. Menyimpan kejutan. Derit, dan juga jerit.
Membicarakan Jakarta memang tak akan pernah usai. Menceritakan Jakarta juga tak akan ada habisnya. Bagi saya, membicarakan Jakarta berarti juga membayangkan kedatangan Bane yang merupakan anggota Liga Bayangan dan juga seorang murid Ra’s Al-ghul. Founder dan Co-founder Liga Bayangan dalam cerita Batman. Dalam trilogi The Dark Knight, Liga Bayangan yang dikomandoi Bane mencoba mengembalikan Gotham dari keterpurukan dengan penghancuran total kota itu untuk kemudian merekonstruksinya dengan tatanan baru. Menyitir Oscar Lange dalam buku Teori Ekonomi Sosialisme, pembangunan ekonomi secara kapitalisme harus dihancurkan total dan dibangun ulang dengan sendi-sendi ekonomi sosialisme. Dan tentu saja itu tak pernah terjadi sekalipun banyak orang yang menaruh harap padanya. Sungguh ironi! Ya, baik Jakarta maupun Gotham sama-sama ironis.
Pada siang yang terik itu saya mengantarkan ibu dari anak saya pergi ke salon untuk potong rambut. Biasanya, saya jarang mengantarnya ke salon karena memang dia jarang meminta saya untuk menemaninya ke salon. Jika pun pergi ke salon seringnya ditemani kakaknya yang juga memang suka sekali nyalon (kalau ini bukan untuk potong rambut). Barangkali dia tahu jika saya tak terlalu menyukai pekerjaan menunggu. Meskipun, untuk sebagian hal tak selalu menunggu itu tak mengasyikkan. Seperti siang ini. Tidak salah lagi.
Sembari menunggu, saya memperhatikan keadaan ruangan salon tersebut. Dua cermin besar dan peralatan untuk menyalon. Tampak juga seorang perempuan terlihat sedang dibasahi rambutnya dengan posisi setengah terbaring, lalu menunggu cairan rambut menyerap sempurna ke dalam keratin. Tangannya juga terlihat mengetik-ngetik sesuatu dengan gawainya. Entah apa yang dilakukannya yang pasti asyik betul.
Setelah pandangan berkelana ke sana ke mari mata saya pun tertuju pada suami dari pemilik salon tersebut yang tengah sibuk mengotak-atik speaker multimedia bermerek GMC yang saya taksir harganya tak lebih dari tiga ratus ribu rupiah, namun mengeluarkan sound yang cukup heavy bass. Sementara istri saya sedang dilayani oleh pemilik salon dan tak ambil pusing dengan semacam pemikiran, musik apakah yang bakal diputar oleh laki-laki itu?
Lagu pun diperdengarkan satu per satu olehnya. Seorang lelaki dengan wajah menanggung waktu mengenakan kaus berkerah sobek di ketiak. Ia memutar bermacam lagu yang semuanya berbahasa inggris. Dari mulai Taylor Swift, Katy Perry, Ariane Grande, hingga Kelly Clarkson yang selalu bertikai dengan saudaranya itu sejak saya SMA. Lagu-lagu tersebut seakan memecah seisi ruang. Jika lagu itu adalah air maka pot-pot tak berbunga yang terkapar di pekarangan salon itu akan penuh olehnya. Sialnya, tak satu pun lagu yang lelaki itu putar sampai tuntas. Ia terus mem-forward lagu demi lagu dengan remote di tangannya, sampai lagu pun terhenti pada beat dengan looping yang berulang-ulang. Saya tak tahu itu lagu siapa namun saya kenal musik yang terdengar kencang itu adalah RnB.
Ada rasa heran yang menganga dalam benak saya saat itu, di kampung kecil yang minat terhadap pendidikan dan literasinya sangat rendah seolah terpatahkan oleh selera musik lelaki yang sudah ujur tersebut. Tak sulit untuk menemukan 8 dari 10 warga di kampung tersebut putus sekolah sejak SD. Tapi tunggu dulu, siapa tahu itu memang playlist anaknya yang dimasukkan ke dalam multimedia GMC itu. Siapa tahu juga ia meminta anaknya yang cukup tahu cara mengunduh lagu-lagu dari internet yang membuat pagi makin punya energi. Karena mungkin saja anaknya telah akrab dengan internet, karena internet mampu menembus ruang-ruang tak terceruk sebelumnya yang membuat William Tanuwijaya berhasil karenanya.
Tapi yang menjadi keheranan saya bukanlah internet melainkan lelaki tua itu, kenapa dia memilih untuk memutar lagu hingga tuntas dengan beat cepat dan looping berulang, bukan malah Taylor Swift yang setidaknya lebih popular di televisi dan radio, misalnya.
Saya lantas teringat dengan buku “Apa Itu Musik?”, yang ditulis Karina Anjani. Menurutnya, terlepas dari definisinya, musik merupakan teman akrab manusia dalam melakukan aktivitasnya. Di toilet, di gorong-gorong, di kemacetan, di kesepian, di kolam ikan, di teras rumah, di kosan, termasuk juga di salon. Ya, orang memang senang mendengarkan musik. Dari 1015 responden, DailySocial.id menyebut 61,48% adalah pencinta musik.
Saya tidak tahu apakah lelaki tua itu termasuk responden DailySocial.id atau bukan. Namun, saya cukup yakin lelaki itu tak tahu apa-apa soal RnB meski mungkin mendengarkannya setiap hari.
Karina, dalam bukunya menjelaskan bahwa definisi musik difragmentasi menjadi tiga hal. Pertama, musik secara intrinsik. Ini berkaitan dengan muatan musik formal yang telah dikenal banyak orang, seperti bunyi yang terdapat dalam tangga nada, tempo, alur dan sejenisnya. Kedua, musik secara subjektif. Saya analogikan begini, tepuk tangan itu musik karena ia membunyikan irama dan ritmis, ya sudah bahwa itu musik. Selesai. Ketiga, musik secara intensional. Ini menitikberatkan pada niatan sebuah suara agar terdengar musikal. Misalnya saja, suara gelas dipukul sendok garpu yang dipadu ember maka ia akan menghasilkan suara yang terdengar musikal, bukan?
Secara umum, Karina melihat musik dari perdebatan tradisi filsafat barat, seperti universal vs partikular. Apakah musik itu adalah sesuatu yang lepas dari dimensi spasio-temporal (universal) ataukah partikular? Merujuk pada hal tersebut jelas dalam benak lelaki tua nan unik itu ia memposisikan musik pada tataran dimensi spasio-temporal alias universal: yang penting asyik, beat-nya enak dan membawa semangat. Sesederhana itu.
Namun, satu hal yang sangat dia sadari yang juga dipahami oleh filsuf pencinta musik, Friedrich Nietzsche, berujar satu waktu: life without music would be a mistake.
Ah, ini sudah pukul 13.30, waktunya kami meninggalkan salon.
You might also like
More from Rehat
Kelemahan Tali Pocong: Simpul yang Gampang Lolos?
Kelemahan Tali Pocong: Simpul yang Gampang Lolos? Tali pocong, sering kali dianggap sebagai senjata pamungkas yang bikin bulu kuduk merinding. Tapi …
Kelemahan Pocong: Menguak Sisi Lemah Si Pembalut Keliling
Kelemahan Pocong: Menguak Sisi Lemah Si Pembalut Keliling Pocong, sosok ikonik dalam mitologi horor Indonesia, kerap digambarkan sebagai makhluk yang melompat-lompat …